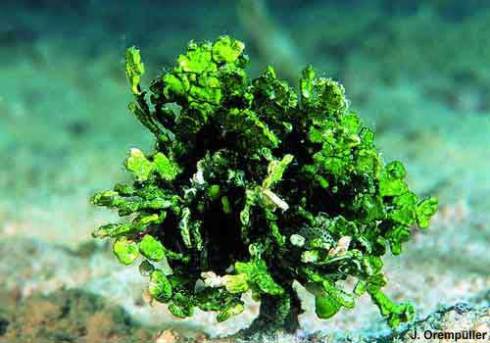Berdasarkan PP 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi bahwa perlu menyesuaikan fungsi koperasi sebagaimana dalam pokok-pokoknya diatur dalam Undang-undang Koperasi dengan jiwa semangat Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi harus diberi peranan sedemikian rupa sehingga gerakan serta penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan:
- alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia;
- sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia,
- dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis,
Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktip dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas Demokrasi Terpimpin dan perlu diadakan Peraturan Pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan Undang-undang Koperasi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi; sehingga terjamin, terpelihara dan terpupuknya dinamika baik dikalangan masyarakat sendiri maupun dalam kalangan petugas negara, serta terselenggaranya koperasi secara serentak, intensip, berencana dan terpimpin.
Berdasarkan PP 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi bagian II tentang penjenisan koperasi yang merupakan pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi. Pada pasal 3 peraturan ini mengutamakan diadakannya jenis-jenis koperasi sebagai berikut:
- Koperasi Desa
- Koperasi Pertanian
- Koperasi Peternakan
- Koperasi Perikanan
- Koperasi Kerajinan/Industri
- Koperasi Simpanan Pinjam
Yang dimaksud Koperasi Perikanan ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan yang bersangkutan dan menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan.
Dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945 perlu segera menyesuaikan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang Koperasi dengan jiwa dari pada Undang-undang Dasar tersebut serta cita-cita yang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pemerintah menyadari bahwa Undang-undang Koperasi yang berlaku sekarang perlu disempurnakan, namun perkembangan masyarakat pada umumnya dan Gerakan Koperasi pada khususnya sedemikian pesatnya sehingga Pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan yang cepat agar pelaksanaan Undang-undang Koperasi dapat berjalan sesuai dengan haluan Pemerintah. Sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, maka koperasi mengambil peranan yang penting sekali sebagai dasar utama untuk mengatur perekonomian rakyat dan selain dari pada itu, Pemerintah memberikan peranan sedemikian rupa sehingga koperasi benar-benar dapat merupakan alat untuk melenyapkan kapitalisme dari bumi dan kehidupan bangsa Indonesia. Dengan menyerahkan saja penyelenggaraan koperasi kepada inisiatip Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang ini bukan tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme tetapi juga tidak terjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya. Kemajuan-kemajuan yang terlihat didalam statistik tentang angka-angka dan jumlah anggota koperasi, jumlah modal dan sebagainya pada hakekatnya masih terlalu pagi untuk dibanggakan, bila kita lihat kenyataan-kenyataan yang kita hadapi dalam praktek sehari-hari.
Gerakan Koperasi dalam taraf perkembangan sekarang ini jauh belum dapat memenuhi fungsi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud didalam pasal 33 Undang-undang 1945 bahkan menunjukkan gejala-gejala yang mempunyai kecenderungan kearah kemerosotan fungsi koperasi dan penyalah-gunaan bentuk usaha koperasi untuk mencari keuntungan bagi segelintir manusia sehingga kepercayaan rakyat terutama didesa-desa semakin lama semakin berkurang terhadap koperasi. Untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan cepat yang sejauh mungkin berpedoman pada ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Koperasi sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa serta semangat Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Berhubung dengan mendesaknya waktu, dalam Peraturan Pemerintah ini belum diatur seluruh materi dari pada Undang-undang Koperasi dan persoalan-persoalan yang timbul dalam praktek dan hanya membatasi pada persoalan-persoalan yang dianggap penting dan mendesak untuk diatur oleh Pemerintah. Untuk menampung persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan-peraturan berikutnya sebagai kelanjutan dari Peraturan Pemerintah ini. Yang menjadi pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Peraturan ini ialah sebagai berikut :
- Azas-azas koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Koperasi perlu diberikan jaminan akan ralisasinya didalam raan koperasi.
- Sikap yang aktip dari Pemerintah,
- Unsur-unsur demokrasi serta ekonomi terpimpin harus jelas terlihat dalam penyelenggaraan tiap-tiap koperasi.
- Segenap instansi Pemerintah diikut-sertakan dalam membimbing Gerakan Koperasi menurut bidangnya masing-masing.
- Terutama dalam lapangan-lapangan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan didaerah-daerah bekerja yang merupakan basis perekonomian rakyat diusahakan berdirinya atau ditumbuhkan koperasi oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat yang bersangkutan.
Dalam pasal tersebut sengaja tidak dipergunakan istilah tidak merupakan konsentrasi modal sebagaimana digunakan dalam perumusan Undang-undang Koperasi untuk mengundang kesulitan didalam menafsirkannya sedang istilah yang dipergunakan ialah “bukan perkumpulan modal” untuk maksud yang sama. Istilah bukan perkumpulan modal diambil dari penjelasan Undang-undang Koperasi dipadang oleh Pemerintah lebih jelas dan tidak mengandung asosiasi pikiran bahwa koperasi telah menganut sesuatu paham golongan dengan tidak mengurangi ketegasan dari pendapat Pemerintah yang berpangkal haluan pada dasar pikiran bahwa koperasi adalah alat utama untuk melenyapkan kapitalisme baik sistimnya maupun ekses-eksesnya.
Mengingat pentingnya peranan koperasi dalam pelaksanaan demokrasi serta ekonomi terpimpin maka harus ada jaminan supaya didalam tubuh organisasi koperasi terdapat kebersihan serta kejujuran dari pada pelaksana-pelaksananya. Untuk ini kecuali kewajiban melaksanakan atas azas koperasi yang dibebankan pada para anggota maka masyarakat didaerah yang bersagkutan perlu memberikan bantuannya. Sesuai dengan sikap Pemerintah yang aktip maka azas keanggotaan koperasi atas dasar suka-rela perlu dijaga agar azas tersebut tidak merupakan pangkal untuk menyelewengkan haluan penyelengggaraan koperasi kearah sistim kapitalisme dan liberalisme. Juga azas gotong-royong mewajibkan semua golongan yang mempunyai peranan dalam proses produksi tertampung atau dapat dimasukkan dalam keanggotaan koperasi.
Oleh karena itu selain ketentuan bahwa yang dapat menjadi anggota sesuai koperasi ialah orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama perlu ditambahkan ketentuan bahwa juga orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung (allied interest) dapat pula menjadi anggota sesuatu koperasi. Dengan demikian dogma pertentangan buruh majikan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bisa dihindarkan didalam perkumpulan koperasi.
Penjenisan koperasi didasarkan pda golongan serta fungsi ekonomi. akan tetapi untuk memudahkan bagi rakyat penjenisan koperasi menurut peraturan ini ditekankan pada lapangan usaha serta tempat tinggal anggota.. Dengan demikian walapun Peraturan ini didasarkan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota dengan ketentuan ayat tersebut terbuka kemungkinan bagi masyrakat untuk mengadakan jenis-jenis koperasi yang berdasarkan golongan serta fungsi ekonomi.
Berdasarkan UU No 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tentang salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan secara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua fihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu, juga perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi-hasil sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu.
Sebagai salah satu usaha menuju ke arah terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di dalam Ketetapan No. II./MPRS/1960 dan Resolusinya No. I/MPRS/1963 memerintahkan supaya diadakan Undang- undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini merupakan realisasi daripada perintah M.P.R.S. tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat 1 Undang- undang Pokok Agraria segala usaha bersama dalam lapangan agraria jadi termasuk juga usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua fihak yang turut serta, yaitu baik nelayan pemilik dan pemilik tambak yang menyediakan kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak maupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang menyumbangkan tenaganya, hingga mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari hasil usaha tersebut.
Pengusahaan perikanan atas dasar bagi hasil dewasa ini adalah diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia belum memberikan dan menjadi bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak. Berhubung dengan itu maka pertama-tama perlu diadakan ketentuan untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan,hingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha itu mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya. Dengan memberikan jaminan yang sedemikian itu maka di samping perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang bersangkutan. diharapkan pula timbulnya perangsang yang lebih besar di dalam meningkatkan produksi ikan. Dalam pada itu hal tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan dari pada pemilik kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak akan diabaikan.Usaha perikanan, terutama perikanan laut, memerlukan pemakaian alat-alat yang memerlukan biaya pemeliharaan serta perbaikan dan yang pada waktunya bahkan harus diganti dengan yang baru. Menetapkan imbangan bagian yang terlalu kecil bagi golongan pemilik biasa berakibat, bahwa soal pemeliharaan dan perbaikan serta penggantian alat-alat tersebut akan kurang mendapat perhatian atau diabaikan sama sekali. Hal yang demikian pula berpengaruh tidak baik terhadap produksi ikan pada umumnya. Berhubung dengan itu para pemilik tersebut harus pula mendapat bagian yang layak, dengan pengertian, bahwa dengan demikian ia berkewajiban pula untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dalam pada itu perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak tidak akan dapat tercapai hanya dengan memperbaiki syarat-syarat perjanjian bagi hasil saja. Untuk itu usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan perlu dipergiat dan lapangan usaha serta keanggotaannya perlu pula diperluas. Keanggotaan koperasi tersebut harus meliputi semua orang yang turut dalam usaha perikanan itu, jadi baik para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan maupun nelayan pemilik dan pemilik tambak. Lapangan usaha koperasi perikanan hendaknya tidak terbatas pada soal produksi saja, misalnya pembelian kapal-kapal/perahu- perahu dan alat-alat penangkapan ikan, pengolahan hasil ikan serta pemasarannya, tetapi harus juga meliputi soal kredit serta hal-hal yang menyangkut kesejahteraan para anggota dan keluarganya. Misalnya usaha untuk mencukupi keperluan sehari-hari, menyelenggarakan kecelakaan, kematian dan lain-lainnya. Dengan demikian maka mereka itu dapatlah dlepaskan dan dihindarkan dari praktek-praktek para pelepas uang. tengkulak dan lain-lainnya, yang dewasa ini sangat merajalela dikalangan usaha perikanan, terutama perikanan laut.
Menurut hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbangan besarnya bagian pemilik pada satu pihak dan para nelayan penggarap serta penggarap tambak pada lain fihak. Perbedaan itu disebabkan selain oleh imbangan antara banyaknya nelayan penggarap dan penggarap tambak pada satu fihak serta kapal/perahu, dan tambak akan dibagi hasilkan pada lain fihak, juga oleh rupa-rupa faktor lainnya Diantaranya ialah penentuan tentang biaya-biaya apa saja menjadi beban bersama dan apa yang dipikul oleh mereka masing-masing. Mengenai perikanan darat di tambak letak, luas keadaan kesuburan tambaknya serta jenis ikan yang dihasilkan merupakan faktor pula yang menentukan imbangan bagian yang dimaksudkan itu. Jika tambaknya subur, maka bagian pemiliknya lebih besar dari pada bagian pemilik tambak yang kurang subur. Mengenai perikanan laut, macam kapal,,perahu dan alat-alat serta cara-cara penangkapan yang dipergunakan merupakan pula faktor yang turut menentukan besarnya imbangan itu. Bagian seorang pemilik kapal motor misalnya, adalah lebih besar imbangan persentasinya. jika dibandingkan dengan bagian seorang pemilik perahu layar. Hal itu disebabkan karena biaya eksploitasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik motor itu lebih besar, lagipula hasil penangkapan seluruhnya lebih besar, hingga biarpun imbangan persentasi bagi para nelayan penggarap lebih kecil, tetapi hasil yang diterima sebenarnya oleh mereka masing-masing adalah lebih besar jika dibandingkan dengan hasil para nelayan penggarap yang mempergunakan kapal/perahu layar.
Berhubung dengan itu di dalam Undang-undang ini bagian yang harus diberikan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum di dalam pasal 3, ditetapkan atas dasar imbangan di dalam pembagian beban-beban dan biaya-biaya usaha sebagai yang tercantum dalam pasal 4. Di daerah-daerah dimana pembagian beban-beban dan biaya-biaya itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam pasal 4, maka tinggal peraturan tentang pembagian hasil sajalah yang harus disesuaikan, yaitu jika menurut kebiasaan setempat bagian para nelayan penggarap atau penggarap tambak masih kurang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3. Jika bagian mereka sudah lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai (pasal 5 ayat 1).
Dengan pengaturan yang demikian itu maka ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil yang dimuat dalam Undang-undang ini dapat segera dijalankan setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dengan tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian dengan keadaan daerah, jika hal itu memang sungguh-sungguh perlu (pasal 5 ayat 2). Mengenai perikanan darat hanya diberi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan bagi hasil tambak. yaitu genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk memelihara ikan, dengan mendapat pengairan yang teratur. Usaha pemeliharaan ikan di empang-empang air tawar dan lain-lainnya tidak terkena Undang-undang ini oleh karena umumnya tidak dilakukan secara bagi hasil, tetapi dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Kalau ada pemeliharaan yang dilakukan secara bagi hasil maka hal itu mengenai kolam-kolam yang tidak luas. Kalau ada sawah yang dibagi hasilkan dan selain ditanami padi juga diadakan usaha pemeliharaan ikan.
Jika melihat perkembangan koperasi perikanan di Indonesia, harus diakui saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Dalam pengertian bahwa sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan pengguna jasanya. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang salah satu-tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Koperasi sangat diharapkan dapat menjadi mitra strategis yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam pengembangan perekonomian. Koperasi akan sangat dirasakan manfaatnya apabila dibuat semakin kuat berdasarkan pondasi yang kokoh. Analoginya kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan hasil maksimal yang terukur. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi.
Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa koperasi baru manis dikonsep tetapi sangat pahit perjuangannya di lapangan. Tidak bisa tidak, pengembangan koperasi barulah sebatas konsep yang indah, namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum, namun kehadirannya tidak membawa manfaat sama sekali. Tentu saja hal ini sangat disayangkan.
Koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global.